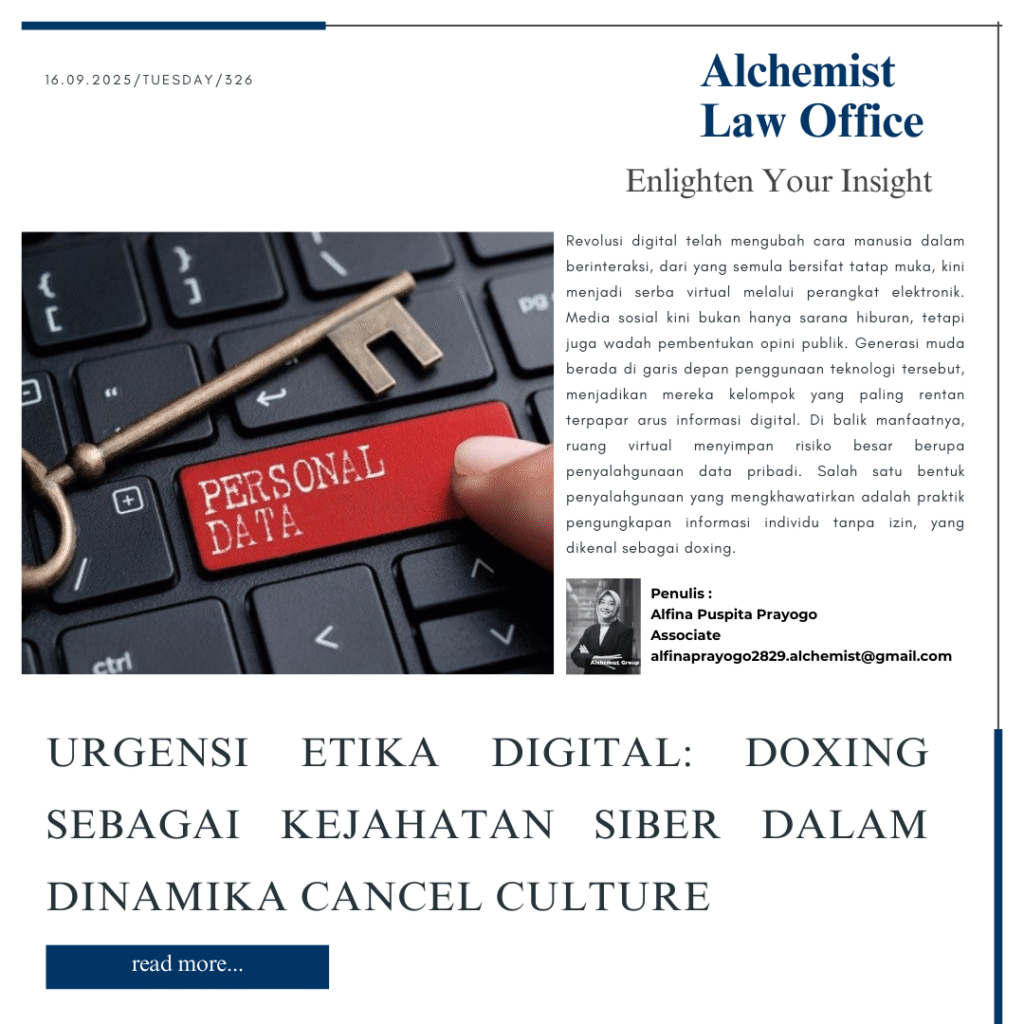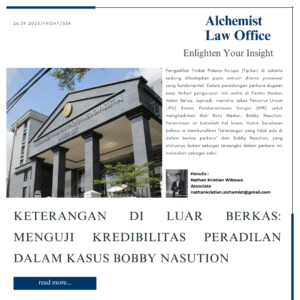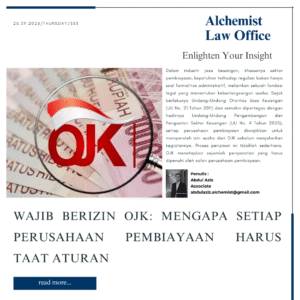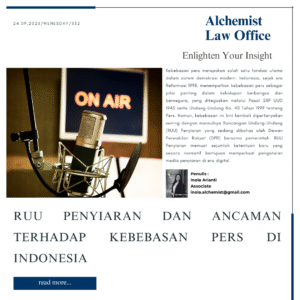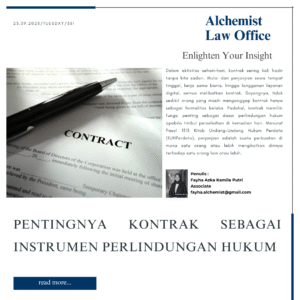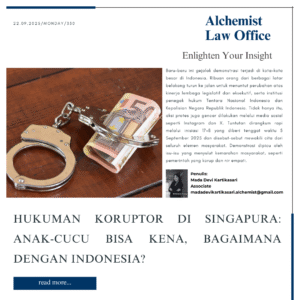Revolusi digital telah mengubah cara manusia dalam berinteraksi, dari yang semula bersifat tatap muka, kini menjadi serba virtual melalui perangkat elektronik. Media sosial kini bukan hanya sarana hiburan, tetapi juga wadah pembentukan opini publik yang mampu memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat secara luas.[1] Generasi muda berada di garis depan penggunaan teknologi tersebut, menjadikan mereka kelompok yang paling rentan terpapar arus informasi digital. Di balik manfaatnya, ruang virtual menyimpan risiko besar berupa penyalahgunaan data pribadi. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang mengkhawatirkan adalah praktik pengungkapan informasi individu tanpa izin, yang dikenal sebagai doxing. Tindakan doxing umumnya dilakukan dengan maksud jahat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menakut-nakuti, menekan, bahkan menimbulkan ancaman terhadap kondisi fisik maupun psikis seseorang. Praktik mengumpulkan serta menyebarkan informasi pribadi jelas merupakan bentuk pelanggaran atas hak privasi individu. Praktik tersebut biasanya muncul dalam bentuk unggahan yang memuat data pribadi, seperti foto, rekaman video, atau narasi tertentu yang sengaja diarahkan guna membentuk serta memengaruhi opini publik.[2]
Fenomena komunikasi digital juga melahirkan budaya sosial baru yang populer dengan istilah cancel culture. Budaya tersebut lahir dari semangat kolektif untuk mengkritik atau menghukum perilaku yang dinilai tidak sesuai dengan standar moral masyarakat. Namun, praktiknya kerap berubah menjadi penghakiman massal yang dilakukan secara serampangan di dunia maya. Akibatnya, individu yang menjadi target sering kali kehilangan martabat, posisi sosial, hingga keamanan personal. Di tengah dinamika cancel culture, doxing menjadi alat yang sering digunakan untuk memperkuat tuntutan sosial. Praktik doxing tersebut tidak sekadar melukai psikologis korban, tetapi juga melanggar prinsip hak asasi manusia karena mengabaikan hak atas privasi. Dalam hukum Indonesia, doxing dapat masuk ke ranah kejahatan siber sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Jadi, tindakan doxing pada dasarnya memiliki konsekuensi hukum yang nyata, tidak hanya sekadar persoalan etika.
Dalam perspektif hukum, doxing termasuk dalam kategori kejahatan siber karena dilakukan melalui media elektronik dan menyerang hak privasi individu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur perlindungan atas data pribadi dalam Pasal 26. Pasal tersebut menyatakan bahwa penggunaan data pribadi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan pemilik data. Undang-Undang ITE memang telah memuat ketentuan mengenai larangan atas tindakan yang berkaitan dengan data pribadi, tetapi permasalahan muncul karena tidak ada penjelasan yang tegas mengenai definisi data pribadi itu sendiri. Akibatnya, apabila ketentuan tersebut dijadikan dasar dalam pengajuan gugatan atau penanganan perkara pidana, pihak penggugat maupun pelapor akan menghadapi kendala dalam proses pembuktian.[3] Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang lebih komprehensif yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi demi terjaminnya kepastian hukum.
Eksistensi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi kemudian memberikan landasan hukum yang lebih kuat, termasuk sanksi administratif dan pidana. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memiliki tujuan untuk memastikan terpenuhinya hak warga negara dalam melindungi dirinya sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai arti penting menjaga data pribadi. Perlindungan data pribadi dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia karena termasuk dalam ruang lingkup perlindungan atas diri individu. Ketentuan mengenai perlindungan diri tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945.
Tindakan doxing dapat dijerat dengan Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
Meskipun sudah ada dasar hukum, penegakan terhadap kasus doxing masih menghadapi tantangan. Salah satu kendala adalah kesulitan melacak pelaku karena identitasnya dapat disamarkan melalui akun anonim. Sebagai akibatnya, banyak korbn doxing tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Padahal, dampak doxing dapat berujung pada teror psikologis yang panjang, bahkan ancaman fisik di dunia nyata. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya efektif tanpa diiringi implementasi yang konsisten.
Fenomena doxing sering kali berkaitan erat dengan budaya cancel culture. Cancel culture yang awalnya dimaksudkan sebagai bentuk kontrol sosial justru berubah menjadi ajang penghakiman massal.[4] Dalam prosesnya, doxing digunakan sebagai senjata untuk memperkuat seruan boikot atau pengucilan. Perkembangan tersebut membawa dampak besar dalam proses transformasi, sehingga perlu disadari bahwa informasi memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat dan harus dilindungi, khususnya yang berkaitan dengan data pribadi.[5]
Cancel culture yang mengandalkan doxing pada dasarnya menciptakan praktik main hakim sendiri di dunia maya. Publik merasa memiliki legitimasi moral untuk menghukum seseorang hanya berdasarkan opini mayoritas. Idealnya, penjatuhan sanksi harus melalui proses peradilan yang menjamin asas praduga tak bersalah. Ketika mekanisme tersebut dilewati, yang muncul adalah bentuk persekusi digital yang merusak tatanan hukum. Dengan kata lain, cancel culture tanpa kendali justru bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan proses hukum formal sebagai jalan penyelesaian utama.
Dalam menghadapi persoalan tersebut, etika digital berperan sebagai pedoman penting. Etika digital mengajarkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang maya tidak boleh meniadakan tanggung jawab terhadap hak orang lain. Prinsip dasar etika tersebut menekankan keseimbangan antara hak untuk berbicara dengan kewajiban menghormati privasi. Dengan menanamkan etika digital, masyarakat dapat memahami bahwa doxing bukan sekadar kesalahan moral, tetapi juga tindak pidana yang merugikan banyak pihak. Literasi digital yang memasukkan aspek hukum dan etika akan membantu generasi muda lebih bijak dalam bermedia sosial.
Urgensi etika digital semakin nyata ketika regulasi saja terbukti belum cukup untuk menekan praktik doxing dalam cancel culture. Penegakan hukum yang kuat harus dibarengi dengan internalisasi nilai etis agar masyarakat mampu melakukan kontrol diri. Etika digital menjadi filter pertama sebelum seseorang memilih untuk menyebarkan informasi di ruang publik. Jika kesadaran etis ini terbangun, maka cancel culture dapat diarahkan menjadi mekanisme kritik sosial yang sehat, bukan persekusi publik. Oleh sebab itu, integrasi antara hukum positif dan etika digital adalah kunci untuk menciptakan ruang digital yang aman, adil, dan berkeadaban.
DAFTAR PUSTAKA
Dade, L. L., et al. (2024). Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (Doxing) di Indonesia. Lex Privatum, 13(3), 1-13.
Muharman, N., et al. (2022). Cancel Culture sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Twitter. Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi, 3(2), 120-135.
Pratiwi, N. & Fitrananda, C. A. (2023). Fenomena Doxing di Media Sosial Twitter (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Mahasiswa Pengguna Twitter di Indonesia). KONTEKSTUAL: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(1), 12-18.
Saly, J. N. & Sulthanah, L. T. (2023). Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Jurnal Kewarganegaraan, 7(2), 1708-1713.
Syuhada, E. A. & Ananta, P. F. (2024). Perlindungan Data Pribadi terhadap Tindakan Doxing dalam Perspektif Hukum Pidana. JURHUM: Jurnal Humaniora, 2(1), 37-46.
[1] Pratiwi, N. & Fitrananda, C. A. (2023). Fenomena Doxing di Media Sosial Twitter (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Mahasiswa Pengguna Twitter di Indonesia). KONTEKSTUAL: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2, 12-18. Diakses dari https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/kontekstual/article/download/3176/2515 pada tanggal 11 September 2025 Pukul 10:59 WIB.
[2] Saly, J. N. & Sulthanah, L. T. (2023). Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Jurnal Kewarganegaraan, 7, 1708-1713. Diakses dari https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5413/3214/15016 pada tanggal 11 September 2025 Pukul 11:18 WIB.
[3] Dade, L. L., et al. (2024). Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (Doxing) di Indonesia. Lex Privatum, 13, 1-13. Diakses dari https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/download/54687/45879 pada tanggal 11 September 2025 Pukul 12:05 WIB.
[4] Muharman, N., et al. (2022). Cancel Culture sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Twitter. Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi, 3, 120-135. Diakses dari https://e-journal.unair.ac.id/MEDKOM/article/download/44044/26393/246936 pada tanggal 11 September 2025 Pukul 13:47 WIB.
[5] Syuhada, E. A. & Ananta, P. F. (2024). Perlindungan Data Pribadi terhadap Tindakan Doxing dalam Perspektif Hukum Pidana. JURHUM: Jurnal Humaniora, 2, 37-46. Diakses dari https://jurhum.umkaba.ac.id/index.php/jamhi/article/download/40/18 pada tanggal 11 September 2025 Pukul 14:54 WIB.