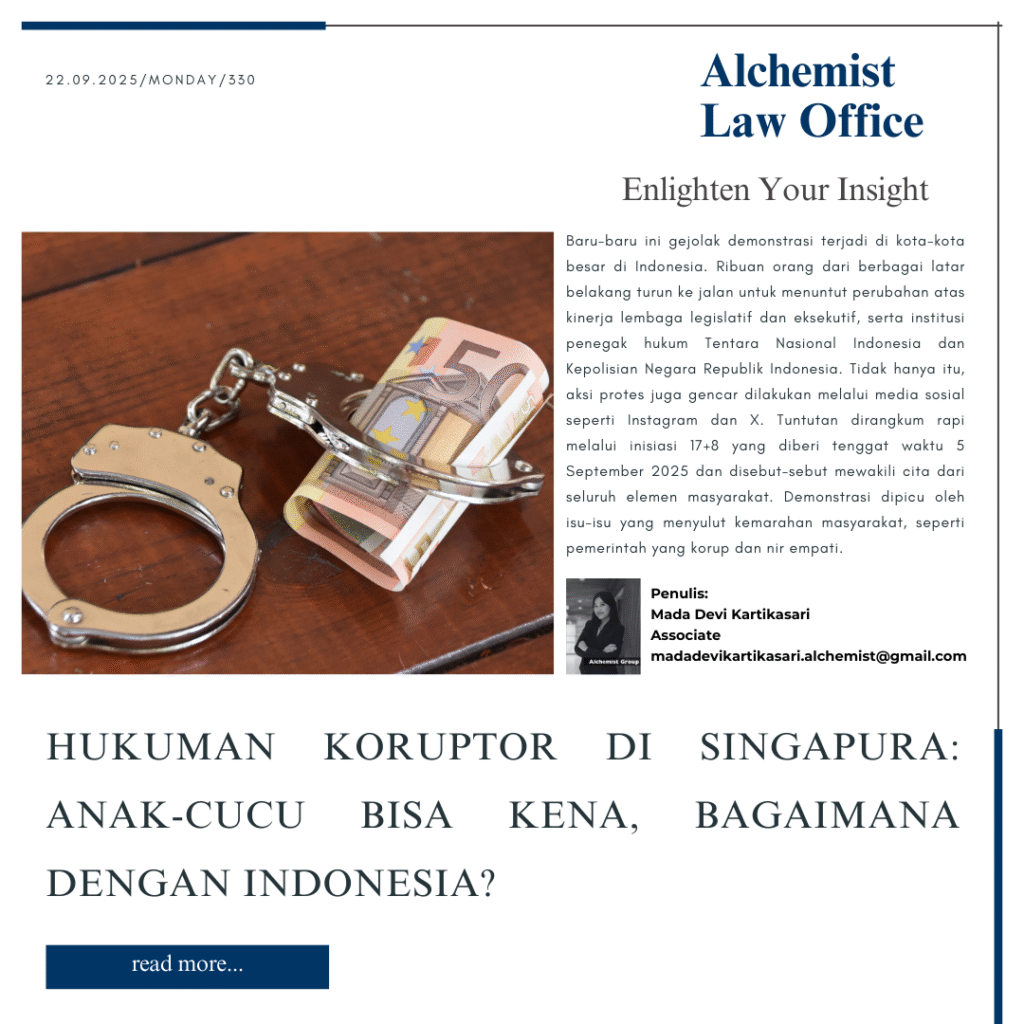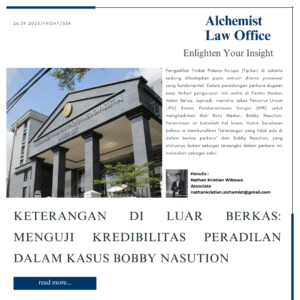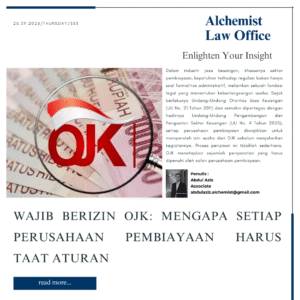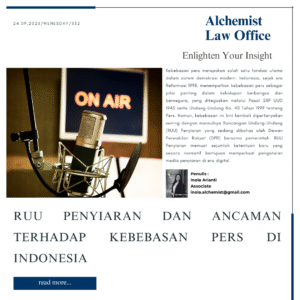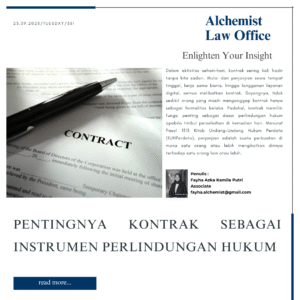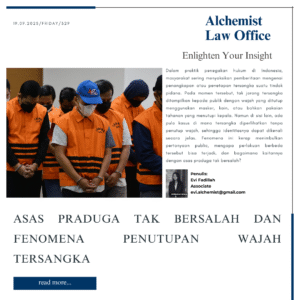Baru-baru ini gejolak demonstrasi terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Ribuan orang dari berbagai latar belakang turun ke jalan untuk menuntut perubahan atas kinerja lembaga legislatif dan eksekutif, serta Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak hanya itu, aksi protes juga gencar dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan X. Tuntutan dirangkum rapi melalui inisiasi 17+8 yang diberi tenggat waktu 5 September 2025 dan disebut-sebut mewakili cita dari seluruh elemen masyarakat.
Demonstrasi dipicu oleh isu-isu yang menyulut kemarahan masyarakat, seperti pemerintah yang korup dan nir empati. Salah satu yang menjadi desakan jangka panjang adalah segera diundangkannya Undang-Undang (UU) Perampasan Aset sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.[1] Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebenarnya telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2015-2019, namun pembahasan mandek hingga 10 tahun berlalu pun UU Perampasan Aset belum juga diundangkan.
RUU Perampasan Aset penting karena berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur tata cara pengembalian kerugian negara agar negara tidak menderita kerugian yang signifikan.[2] Berdasarkan naskah akademiknya, UU Perampasan Aset nantinya menyasar segala aset yang menjadi sarana melakukan tindak pidana serta keuntungan dari tindak pidana tersebut.[3] Artinya, perampasan aset terfokus pada aset yang berkaitan dengan tindak pidana, bukan aset pribadi pelaku tindak pidana.[4] Perampasan akan menyasar aset yang berada di dalam maupun di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia, untuk yang terakhir akan melalui mekanisme kerjasama internasional.[5]
Faktanya, saat ini ketentuan hukum perampasan aset telah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). UU Tipikor mengatur perampasan aset sebagai pidana tambahan, dengan aset berupa barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana korupsi dilakukan, serta barang-barang penggantinya.[6] Ini termasuk tanah, bangunan, kendaraan, perusahaan beroperasi maupun perusahaan cangkang. Apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan padahal terdapat bukti yang cukup kuat atas tindak pidana yang dilakukan olehnya, maka hakim dapat menetapkan perampasan atas barang-barang yang telah disita.[7]
Meski demikian, ketentuan hukum perampasan aset tersebut belum kuat karena tidak mengatur syarat-syarat perampasan aset secara menyeluruh. Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor merupakan norma yang kabur (vague van normen) karena tidak mengatur dengan jelas batasan dan kriteria aset yang dapat dirampas.[8] Ketentuan perampasan aset bagi terdakwa yang meninggal dunia sebagaimana diatur Pasal 38 ayat (5) UU Tipikor juga terbatas pada barang yang telah disita saja. Sedangkan, terhadap barang yang belum disita padahal di kemudian hari dapat diketahui digunakan untuk atau diperoleh dari korupsi, tidak terdapat ketentuan hukumnya. Kemudian, terhadap barang yang bukan milik terdakwa tidak dapat dijatuhkan putusan pengadilan apabila menyebabkan hak pihak ketiga yang beritikad baik dirugikan. Ketentuan tersebut memberi limitasi atas perampasan aset yang secara hukum tercatat atas nama orang lain selaku nominee, namun kekuasaan asli untuk menikmati manfaat dari aset tersebut dipegang oleh beneficiary-nya, yang dalam hal ini terdakwa korupsi.[9]
Selain itu, apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, dan telah ada kerugian keuangan negara secara nyata, maka berkas perkara atau salinan berkas berita acara sidang diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.[10] Ketentuan tersebut tidak secara langsung mengatur tentang perampasan aset, melainkan keharusan menempuh upaya hukum baru berupa gugatan perdata yang semakin memperpanjang proses pengembalian kerugian negara.
Mari menelaah ketentuan hukum di negara tetangga yang telah menyandang status negara maju, yaitu Singapura. Pada 2024, Singapura memperoleh skor Corruption Perceptions Index (CPI) sebesar 84 dan menjadi peringkat ke-3 dari 180 negara. CPI merupakan metrik yang disusun oleh Transparency International untuk mengukur tingkat korupsi sektor publik dari suatu negara dengan skor tertinggi 100.[11] Sementara itu, Indonesia memperoleh skor 37 dengan peringkat ke-99. Senjangnya skor Singapura dan Indonesia dalam penilaian tingkat korupsi sektor publik menjadi salah satu penanda bahwa tatanan hukum korupsi Singapura jauh lebih baik.
Hukum perampasan aset Singapura diatur dalam Corruption, Drug Trafficking, and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (CDSA). Section 7(1) CDSA menetapkan bahwa pengadilan, atas permohonan Jaksa Penuntut Umum (JPU), wajib menjatuhkan perintah perampasan terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana serius, sehubungan dengan manfaat yang diperolehnya dari tindak pidana, jika pengadilan meyakini bahwa manfaat tersebut memang diperoleh dari tindak pidana tersebut.[12] Section 7(6)(7) CDSA bahkan mengatur ruang lingkup dan mekanisme penentuan aset yang dapat dirampas sebagai berikut:
- setiap orang yang memiliki atau
- pada waktu tertentu pernah memiliki
- suatu harta benda atau
- kepentingan atas suatu harta benda,
- termasuk pendapatan yang timbul dari harta benda atau kepentingan tersebut,
- yang tidak seimbang dengan sumber penghasilan yang diketahui orang tersebut, dan
- kepemilikan tersebut tidak dapat dijelaskan secara memuaskan kepada pengadilan,
- maka hingga terbukti sebaliknya,
- dianggap telah memperoleh manfaat dari tindak pidana.
- Selain itu, setiap pengeluaran oleh orang tersebut,
- hingga terbukti sebaliknya,
- dianggap telah dibiayai dari manfaat yang diperoleh orang tersebut dari tindak pidana.[13]
Pengadilan menafsirkan istilah “harta benda atau kepentingan atas suatu harta benda” secara luas, mencakup uang yang ada pada rekening bank terdakwa, uang tunai, deposit yang dilakukan terdakwa ke rekening bank orang tuanya, mobil, pengeluaran untuk makanan, transportasi, asuransi mobil, serta tunjangan ke orang tua terdakwa.[14]
Kenny Foo berpendapat bahwa dalam menentukan suatu harta benda merupakan manfaat dari tindak pidana atau bukan, Singapura melakukan 5 tahap identifikasi yang terdiri dari:
- Identifikasi aset;
- Valuasi atau penilaian aset;
- Perbandingan aset dengan sumber penghasilan terdakwa;
- Penjelasan oleh terdakwa untuk menerangkan asal kepemilikan aset jika tidak proporsional dengan jumlah penghasilannya;
- Simpulan oleh pengadilan mengenai status aset (sebagai manfaat dari tindak pidana atau bukan), yang bergantung pada seberapa jelas atau memuaskannya penjelasan terdakwa.[15]
JPU mengemban beban pembuktian awal atas aset yang tidak proporsional dengan jumlah penghasilan. Kemudian, beban tersebut beralih ke terdakwa untuk menjelaskan alasan kepemilikan aset yang tidak proporsional hingga meyakinkan pengadilan.[16]
Selain itu, CDSA juga mengatur perampasan aset dalam hal terdakwa meninggal dunia secara lebih komprehensif daripada hukum Indonesia. Dinyatakan dalam CDSA, proses hukum akan tetap berjalan dan menyasar wakil pribadi terdakwa yang meninggal dunia atau ahli waris yang berhak atas harta peninggalan terdakwa yang meninggal dunia, sebagaimana ditentukan oleh pengadilan atas permohonan JPU.[17] Artinya, upaya hukum yang sedang berjalan tidak akan diberhentikan sehingga tidak perlu menempuh upaya hukum baru. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 33 jo. Pasal 34 UU Tipikor yang mengatur dilakukannya upaya hukum baru berupa gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa.
Aset yang dapat dirampas termasuk aset yang kepemilikannya dimulai sejak awal periode 6 (enam) tahun yang berakhir pada tanggal kematian terdakwa.[18] Kemudian, ketentuan hukum mengenai terdakwa yang meninggal dunia ditujukan kepada ia yang meninggal dunia:
- setelah penyidikan atas tindak pidana korupsi telah dimulai terhadap dirinya;
- sebelum proses peradilan atas tindak pidana tersebut diajukan, atau apabila proses peradilan tersebut telah diajukan, sebelum ia dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut.[19]
Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa Singapura telah memiliki mekanisme perampasan aset yang lebih komprehensif dibandingkan Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dalam menyusun UU Perampasan Aset diharapkan dapat mempelajari kelebihan-kelebihan dalam kerangka hukum perampasan aset Singapura maupun negara-negara lain yang patut menjadi percontohan. Sembari itu, mari kita terus kawal RUU Perampasan Aset agar masuk ke daftar Prolegnas 2026 dan menjadi prioritas pembahasan.
Daftar Rujukan:
- Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Corruption, Drug Trafficking, and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992.
2. Putusan Pengadilan
Public Prosecutor v Abdul Kahar bin Othman, (2021), SGHC 23 (Putusan Mahkamah Agung Singapura Nomor 23).
3. Jurnal
Adam, Widyarti. “Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis 5. (No. 1, 2025). Hlm. 151-161.
Foo, Kenny. “Money Laundering Offences Under the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act.” Singapore Academy of Law Journal 29. (2017). Hlm. 163-193.
Pranoto, Agus, Abadi B. Darmo, Iman Hidayat. “Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Legalitas 10. (No. 1, 2018). Hlm. 91-121.
Wicaksono, Lucky Suryo. “Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 23. (No. 1, 2016). Hlm. 42-57.
4. Artikel/Berita dari Internet
BBC News Indonesia. “Apa itu tuntutan 17+8? – Mahasiswa akan terus demo sampai tuntutan dipenuhi, DPR berikan tanggapan.” bbc.com. 4 September 2025. Tersedia pada https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqxzjq7rwxyo. Diakses pada 11 September 2025.
Corruption Perception Index. “CPI 2024: Highlights and Insights.” transparency.org, 2025. Tersedia pada https://www.transparency.org/en/news/cpi-2024-highlights-insights-corruption-climate-crisis?gad_source=1&gad_campaignid=15272914516&gbraid=0AAAAADud0D9JgtCgsdG4zUQ6WftYs6497&gclid=CjwKCAjwz5nGBhBBEiwA-W6XRLOILLWLi822p4RPCkoqLVa7angHMITZSaqGeV4E9i8STEQqeJL4gBoC1PoQAvD_BwE. Diakses pada 15 September 2025.s
Indonesia Corruption Watch. “RUU Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset yang Disalahgunakan.” antikorupsi.org. 12 Oktober 2023. Tersedia pada https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan. Diakses pada 11 September 2025.
Thuraisingam, Eugene. “Snapshot: asset confiscation in Singapore.” lexology.com. 3 Oktober 2022. Tersedia pada https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c85f7f46-439f-4a9b-a2c5-69af62778b61&utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 17 September 2025.
5. Lainnya
Badan Pembinaan Hukum Nasional. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2022.
[1] BBC News Indonesia, “Apa itu tuntutan 17+8? – Mahasiswa akan terus demo sampai tuntutan dipenuhi, DPR berikan tanggapan”, bbc.com, 4 September 2025, tersedia pada https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqxzjq7rwxyo, diakses pada 11 September 2025.
[2] Indonesia Corruption Watch, “RUU Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset yang Disalahgunakan”, antikorupsi.org, 12 Oktober 2023, tersedia pada https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan, diakses pada 11 September 2025.
[3] Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022, hlm. 242, selanjutnya disebut Naskah Akademik RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.
[4] Widyarti Adam, “Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis 5, (No. 1, 2025), hlm. 159.
[5] Naskah Akademik RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, hlm. 243.
[6] Pasal 18 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut UU Tipikor.
[7] Pasal 38 ayat (5) UU Tipikor.
[8] Agus Pranoto, Abadi B. Darmo, Iman Hidayat, “Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Legalitas 10, (No. 1, 2018), hlm. 95.
[9] Lucky Suryo Wicaksono, “Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 23, (No. 1, 2016), hlm. 48.
[10] Pasal 33 jo. Pasal 34 UU Tipikor.
[11] Corruption Perception Index, “CPI 2024: Highlights and Insights”, transparency.org, 2025, tersedia pada https://www.transparency.org/en/news/cpi-2024-highlights-insights-corruption-climate-crisis?gad_source=1&gad_campaignid=15272914516&gbraid=0AAAAADud0D9JgtCgsdG4zUQ6WftYs6497&gclid=CjwKCAjwz5nGBhBBEiwA-W6XRLOILLWLi822p4RPCkoqLVa7angHMITZSaqGeV4E9i8STEQqeJL4gBoC1PoQAvD_BwE, diakses pada 15 September 2025.
[12] Section 7(1) Corruption, Drug Trafficking, and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992, selanjutnya disebut CDSA.
[13] Section 7(6)(7) CDSA.
[14] Public Prosecutor v Abdul Kahar bin Othman, (2021), SGHC 23, paragraf 13(b)(c).
[15] Kenny Foo, “Money Laundering Offences Under the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act”, Singapore Academy of Law Journal 29, (2017), hlm. 166-167.
[16] Eugene Thuraisingam, “Snapshot: asset confiscation in Singapore”, lexology.com, 3 Oktober 2022, tersedia pada https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c85f7f46-439f-4a9b-a2c5-69af62778b61&utm_source=chatgpt.com, diakses pada 17 September 2025.
[17] Section 31(1) CDSA.
[18] Section 6(a) CDSA.
[19] Section 7(a)(b) CDSA.