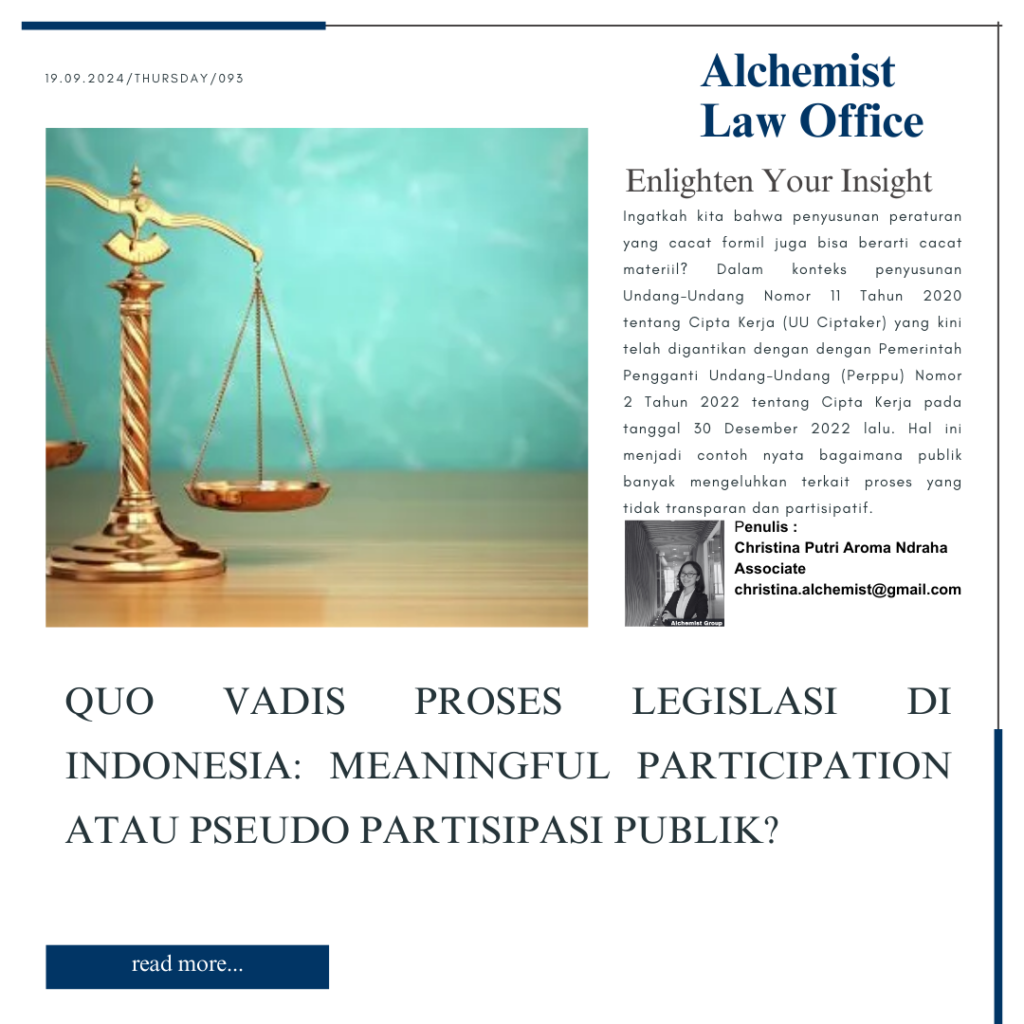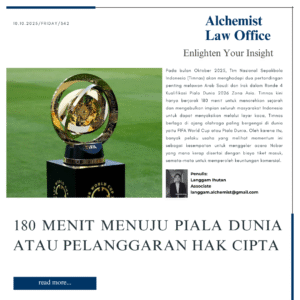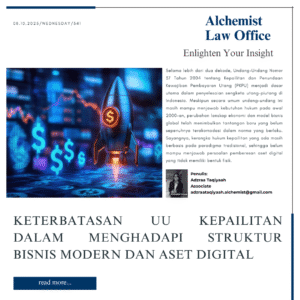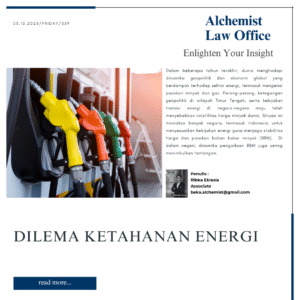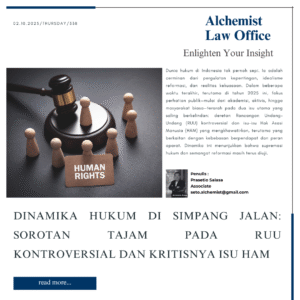Ingatkah kita bahwa penyusunan peraturan yang cacat formil juga bisa berarti cacat materiil? Dalam konteks penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang kini telah digantikan dengan dengan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022 lalu. Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana publik banyak mengeluhkan terkait proses yang tidak transparan dan partisipatif berdampak pada substansi peraturan yang dihasilkan. Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang diposisikan sebagai bagian dari komitmen terhadap produk legislasi yang bertanggung jawab secara sosial. Proses legislasi tersebut harus dibuat dalam kerangka mengatasi permasalahan sosial serta harus berpihak pada kelompok rentan.
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatoris menjadi suatu wujud keterlibatan warga negara. Utamanya dalam memastikan produk legislasi dapat dibentuk dengan memenuhi materi muatan yang sejalan dengan kepentingan publik dan tidak bertentangan dengan konstitusi maupun perundang-undangan yang ada. Namun dalam perkembangannya di Indonesia, sejumlah fakta dalam pergulatan demokratisasi mulai banyak ditemukan, utamanya pada pembentukan peraturan perundang-undangan mengesampingkan partisipasi publik.
Dalam polemik Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 terkait judicial review atau pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, dan kini digantikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022, sebagai pengganti UU Ciptaker.
Putusan yang menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional tersebut, telah menjelaskan melalui pertimbangan hakim (ratio decidendi) bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui partisipasi masyarakat yang bermakna. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal cacat formil terutama terkait keterlibatan masyarakat, sebagaimana diungkapkan Feri Amsari “Dalam sembilan amar putusan MK tidak ada perintah untuk merevisi UU P3. Semua soal perbaikan UU Cipta Kerja.” Partisipasi publik dalam perencanaan UU P3 yang minim sehingga tidak memenuhi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh UU P3. Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan bahwa partisipasi publik yang dilakukan haruslah partisipasi publik yang substansial atau bermakna (meaningful participation). Setidaknya, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu partisipasi publik memenuhi meaningful participation menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan di atas. Pertama, hak untuk didengarkan. Kedua, hak untuk dipertimbangkan. Ketiga, hak untuk mendapatkan. Namun menurut Muslim Silaen, dalam perbaikan UU P3, pemerintah tidak dapat memenuhi ketiga syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi.
Selanjutnya adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 merupakan judicial review yang diajukan empat pemohon dari kalangan akademisi dan aktivis, terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), dengan dalil permohonan yang berpusat pada proses perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung yang diduga mencirikan deviasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, berkisar pada isu partisipasi, pembahasan tertutup, hingga muncul kesan mengejar kepentingan tertentu. Bahkan hingga muncul dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik dalam prosedural dan proses formal Undang-Undang Mahkamah Agung.
Lebih dalam, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah dijelaskan terkait partisipasi masyarakat, secara spesifik pada Pasal 96:
Ayat (1) “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”
Ayat (2) “Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- Rapat dengar pendapat umum;
- Kunjungan kerja;
- Sosialisasi, dan/atau
- Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
Berkaitan dengan ketentuan tersebut, Arnstein dalam bukunya A Ladder of Citizen Participation mengungkapkan bahwa selama ini banyak keterlibatan masyarakat yang diukur berdasarkan angka, seperti jumlah partisipan dan jumlah-jumlah dan sosialisasi yang sengaja dibuat untuk memenuhi target angka semata.
Namun, pada akhirnya angka-angka tersebut tidak begitu bermakna, di mana kita tidak mengetahui koneksi seperti apa yang terjadi di dalamnya, sejauh mana partisipasi masyarakat yang hadir dalam forum-forum sosialisasi dan pertemuan tersebut dipertimbangkan.
Pada dua anak tangga terbawah terdapat manipulasi dan terapi yang menggambarkan bentuk non-partisipasi yang telah dirancang agar seakan menggantikan partisipasi sejati. Publik diberi wewenang seakan mereka punya bagian dalam proses untuk menyangkal kekuasaan, yang sebenarnya semua itu hanyalah partisipasi semu.
Naik satu tangga pada memasuki fase “tokenism” yang terdiri dari tiga anak tangga “informasi”, “pembentukan” dan “pertimbangan”. Pemegang kekuasaan menyebarkan informasi untuk meyakinkan bahwa adanya “keterbukaan” di dalam proses keberjalan suatu sistem. Benar adanya bahwa pemberian informasi adalah pintu pertama menuju partisipasi warga negara yang sah. Tetapi akan sangat berbahaya ketika publik tidak menyadari bahwa informasi yang diberikan adalah narasi dangkal penenang publik dan sifatnya seringkali satu arah.
Sedangkan pada tahap “pembentukan” dan “pertimbangan” lebih memungkinkan bagi mereka yang tidak mampu untuk bersuara dan mendengar, tetapi dalam kondisi ini gerak dan suara publik akan tetap dibatasi oleh kekuasaan itu sendiri. Sehingga apa yang disuarakan sifatnya tidak berkelanjutan dan tidak ada jaminan untuk mengubah status quo.
Tahap “tokenism” inilah yang banyak diterapkan di Indonesia, yang secara aturan dasar menuliskan bahwa publik berhak memberikan permintaan, masukan dan saran kepada pemerintah serta sebaliknya pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan kepada publik, tetapi tetap terbatas dengan adanya kekuasaan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan sistem pemerintahan yang ada.
Setidaknya ada tiga asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diabaikan dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja, yakni asas keterbukaan, asas kejelasan rumusan, dan asas kedayagunaan. Keterbukaan adalah syarat mutlak dalam proses demokrasi, terutama dalam pembentukan kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Ketika proses ini dilakukan secara tertutup, publik kehilangan kepercayaan terhadap produk hukum yang dihasilkan.
Proses yang cacat ini, dalam banyak kasus, berpotensi menghasilkan produk hukum yang cacat pula. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak pihak menggunakan yang mulai tidak percaya akan proses legislasi saat ini. Ketidakpercayaan ini bukan hanya berdasarkan substansi undang-undang, tetapi juga pada proses pembentukannya yang dinilai jauh dari prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat yang seharusnya dijunjung tinggi.
Konstitusionalitas sebuah undang-undang tidak hanya ditentukan oleh materi muatannya, tetapi juga oleh cara undang-undang tersebut dibentuk. Proses yang melibatkan partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas adalah indikator penting dari sebuah regulasi yang baik. Menolak undang-undang yang cacat secara prosedural adalah sebuah langkah yang sah dalam upaya menjaga konstitusionalitas suatu negara. Jika prosedur sudah tidak benar, maka produk yang dihasilkan akan diragukan keabsahannya.
Bukan berarti semua materi muatan yang terkandung dalam UU Cipta Kerja tidak memiliki aspek positif. Tentu ada dampak yang baik dari beberapa pasalnya, terutama dalam upaya meningkatkan kemudahan berusaha dan menarik investasi asing. Namun, dampak baik tersebut tidak akan berarti jika proses pembentukan undang-undangnya cacat. Proses adalah fondasi dari produk yang dihasilkan, dan jika fondasi itu rapuh, produk tersebut akan sulit bertahan.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus memperjuangkan partisipasi yang bermakna dalam setiap proses pembuatan kebijakan, termasuk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Partisipasi publik yang luas dan keterbukaan adalah kunci untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dijalankan dengan itikad baik. Lagipula, proses yang adil akan mencerminkan niat baik dari setiap peraturan yang dibuat.