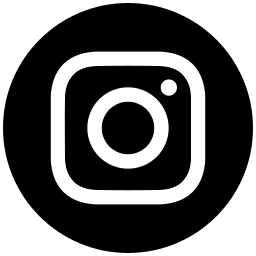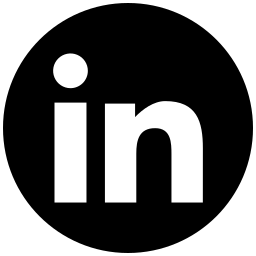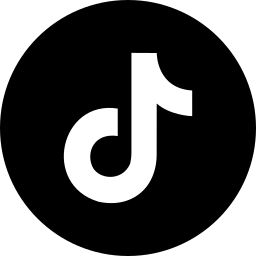Reformulasi Penanganan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia : Deferred Prosecution Agreement (DPA):
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (KUHAP Baru) memperkenalkan Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai instrumen baru dalam penanganan tindak pidana korporasi. Mekanisme ini menandai pergeseran strategi penegakan hukum pidana terhadap korporasi di Indonesia.
Secara konseptual, DPA memungkinkan Penuntut Umum menangguhkan penuntutan terhadap korporasi dengan syarat korporasi memenuhi kewajiban tertentu yang dituangkan dalam perjanjian dan diawasi oleh pengadilan. Berbeda dengan litigasi konvensional yang berorientasi pada pemidanaan, DPA menekankan pemulihan kerugian, reformasi tata kelola, serta peningkatan kepatuhan hukum sebagai tujuan utama.
Problematika Penegakan Hukum Korporasi
Penanganan tindak pidana korporasi selama ini menghadapi hambatan sistemik, termasuk proses pembuktian yang kompleks, waktu yang panjang, dan biaya tinggi. Struktur organisasi yang rumit serta pemisahan tanggung jawab menyulitkan pembuktian kesalahan korporasi. Selain itu, sistem pemidanaan yang berfokus pada individu pengurus tidak selalu menghasilkan pemulihan kerugian negara atau korban secara optimal. Proses peradilan yang berlarut-larut sering kali meningkatkan biaya sosial dan fiskal tanpa restitusi yang memadai, sehingga diperlukan mekanisme alternatif yang menggabungkan efisiensi, kepastian hukum, dan pemulihan substantif.
Pergeseran Global dan Praktik Internasional
DPA telah berkembang secara luas dalam praktik internasional. Amerika Serikat memelopori penerapannya melalui kebijakan US Department of Justice, khususnya dalam kasus korupsi lintas negara dan pelanggaran FCPA. Inggris mengadopsinya melalui Crime and Courts Act 2013 dengan supervisi pengadilan, diikuti Prancis melalui Sapin II Law (2016) dan Singapura melalui reformasi hukum acaranya.
Keberhasilan model ini tercermin dalam penyelesaian kasus besar seperti Rolls-Royce, Airbus, dan Siemens, yang menghasilkan pembayaran denda miliaran dolar disertai kewajiban reformasi internal tanpa proses litigasi panjang. Praktik tersebut menunjukkan bahwa DPA dapat menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum, kepastian usaha, dan pemulihan kerugian.
Evolusi Pengaturan di Indonesia
Sebelum KUHAP Baru, hukum acara pidana Indonesia (UU No. 8 Tahun 1981) tidak mengenal mekanisme penundaan penuntutan berbasis perjanjian. Walaupun konsep keadilan restoratif berkembang melalui Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, regulasi tersebut secara eksplisit mengecualikan perkara korporasi. Kekosongan inilah yang kemudian diisi melalui pengaturan DPA dalam Pasal 328 KUHAP Baru.
Mekanisme DPA dalam Pasal 328 KUHAP Baru
Pasal 328 ayat (1)–(17) mengatur penerapan DPA yang hanya berlaku bagi tindak pidana korporasi dengan tiga tujuan utama: perbaikan kepatuhan hukum, pemulihan kerugian, dan efisiensi peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan korporasi kepada Penuntut Umum sebelum pelimpahan perkara ke pengadilan. Penuntut Umum memiliki diskresi untuk menerima atau menolak permohonan dengan mempertimbangkan keadilan, kepentingan korban, dan tingkat kepatuhan korporasi.
Jika disetujui, dilakukan negosiasi isi perjanjian yang dapat mencakup pembayaran restitusi, pelaksanaan program compliance, kerja sama penegakan hukum, dan tindakan korektif lainnya. Perjanjian tersebut harus disahkan pengadilan setelah diuji legalitas dan proporsionalitasnya. Pemenuhan kewajiban mengakibatkan penghentian perkara, sedangkan kegagalan dapat menyebabkan pembatalan perjanjian dan dilanjutkannya penuntutan.
Catatan Kritis dan Tantangan Implementasi
Meskipun progresif, pengaturan DPA masih menyisakan celah, terutama terkait minimnya desain teknis pengawasan pengadilan dan luasnya diskresi Penuntut Umum melalui penggunaan frasa “dapat”. Tanpa pedoman objektif dan standar minimum yang jelas, DPA berpotensi disalahgunakan dan memunculkan kritik sebagai bentuk “justice for sale”, yakni penghindaran pemidanaan melalui kompromi finansial.
Karena itu, diperlukan regulasi turunan berupa Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Jaksa Agung untuk menetapkan standar klausula, mekanisme monitoring, serta parameter transparansi. Pada akhirnya, efektivitas DPA sebagai instrumen keadilan substantif sangat bergantung pada pengawasan yudisial yang kuat, integritas aparat penegak hukum, dan transparansi proses. Tanpa prasyarat tersebut, DPA berisiko menjadi sekadar kompromi prosedural, bukan reformasi penegakan hukum yang bermakna.
Referensi :
-
Pasal 328 UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
-
US Department of Justice, Justice Manual: Principles of Federal Prosecution of Business Organizations (2020).
-
United Kingdom, Crime and Courts Act 2013, Schedule 17 (Deferred Prosecution Agreements).
-
France, Law No. 2016-1691 (Sapin II); Singapore Criminal Procedure Code reforms on corporate resolution mechanisms.
-
OECD, Resolving Foreign Bribery Cases with Non-Trial Agreements (OECD Publishing, 2019).
-
Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020.
-
Brandon L. Garrett, Too Big to Jail: How Prosecutors Compromise with Corporations (Harvard University Press, 2014).
Penulis : Arrivan Utama
Jabatan : Senior Associate




.png.webp)