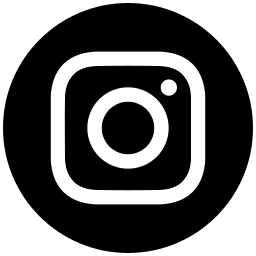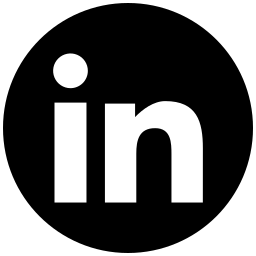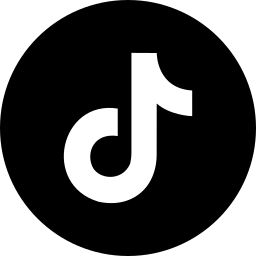OTT Wakil Tuhan di Bumi: Tamparan Keras bagi Wajah Peradilan
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pimpinan Pengadilan Negeri (PN) Depok pada Februari 2026 menjadi pukulan keras bagi wajah peradilan Indonesia. Keterlibatan hakim dalam praktik suap bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap prinsip negara hukum dan amanah profesi hakim sebagai penegak keadilan.
Dalam perkara sengketa lahan di Depok, Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta, dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, diduga meminta imbalan sebesar Rp1 miliar untuk memuluskan proses hukum, yang kemudian disepakati menjadi Rp850 juta. Namun persoalan ini tidak berhenti pada transaksi suap semata.
KPK mengungkap bahwa Wakil Ketua PN Depok diduga menyusun resume pelaksanaan eksekusi riil yang menjadi dasar penetapan putusan pengosongan lahan pada 14 Januari 2026. Fakta ini menunjukkan bahwa suap tersebut secara langsung memengaruhi substansi putusan. Korupsi tidak lagi berada di pinggiran proses hukum, melainkan masuk ke inti pengambilan keputusan peradilan.
Selain dua pimpinan pengadilan, KPK juga menetapkan seorang juru sita PN Depok, Direktur Utama PT KD, dan Head Corporate Legal PT KD sebagai tersangka. Keterlibatan berbagai pihak ini mengindikasikan adanya pola yang terstruktur, baik dari internal pengadilan maupun dari pihak pemohon perkara. Hal tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa praktik serupa mungkin bukan tindakan individual semata.
Pernyataan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, yang akan menelusuri kemungkinan keterlibatan pimpinan PN Depok sebelum periode kepemimpinan saat ini, memperkuat dugaan bahwa kasus ini dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap praktik yang lebih luas. Jika terbukti berlangsung lintas periode, maka persoalannya tidak lagi bersifat sporadis, melainkan berpotensi sistemik.
Kasus ini berdampak serius terhadap kepercayaan publik. Hakim sering disebut sebagai “wakil Tuhan di bumi” karena kewenangannya menentukan nasib dan hak seseorang melalui putusan. Ketika kewenangan tersebut diperjualbelikan, legitimasi moral dan institusional peradilan ikut runtuh. Bahkan, putusan-putusan yang dihasilkan sebelumnya pun berisiko dipertanyakan integritasnya.
Situasi ini menjadi refleksi atas upaya reformasi peradilan yang telah dilakukan selama ini. Berbagai pembenahan administratif dan sistem pengawasan memang telah diterapkan, namun kasus OTT PN Depok menunjukkan bahwa reformasi struktural saja belum cukup. Tanpa integritas individu dan budaya kelembagaan yang kuat, celah penyalahgunaan kewenangan tetap terbuka.
Langkah tegas KPK patut diapresiasi sebagai bagian dari pemberantasan korupsi di sektor peradilan. Namun, upaya tersebut perlu diiringi reformasi internal yang lebih mendalam di lingkungan Mahkamah Agung. Penguatan pengawasan internal, audit putusan secara acak, rotasi hakim secara berkala, serta perlindungan bagi pelapor pelanggaran (whistleblower) harus menjadi prioritas.
Di samping itu, reformasi kultural menjadi kebutuhan mendesak. Pendidikan etika profesi yang berkelanjutan dan sistem rekrutmen berbasis integritas harus diperkuat untuk memastikan bahwa hanya individu dengan komitmen moral tinggi yang menduduki jabatan strategis di peradilan. Peran masyarakat sipil dan media dalam mengawasi proses peradilan juga penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Pada akhirnya, OTT PN Depok harus dimaknai sebagai momentum evaluasi menyeluruh. Penegakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih, disertai pembenahan struktural dan kultural, menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik. Reformasi peradilan tidak boleh berhenti pada penanganan kasus, tetapi harus menyentuh akar persoalan integritas di lingkungan lembaga peradilan.
Penulis : Nathan Kristian Wibowo
Jabatan : Associate




.png.webp)