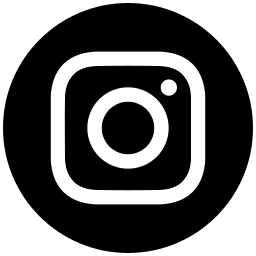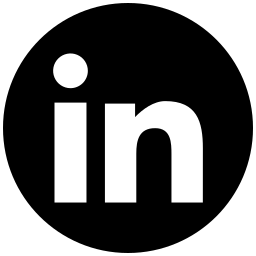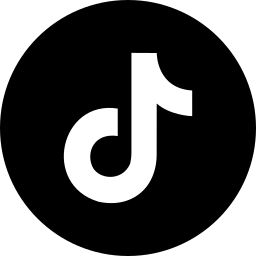Korban Kejahatan yang Justru Diproses Pidana
Fenomena korban kejahatan yang justru diproses sebagai pelaku pidana kembali menjadi sorotan serius dalam praktik penegakan hukum Indonesia. Dalam sejumlah kasus begal dan penjambretan, pola yang muncul berulang: korban atau pihak yang membela korban ditetapkan sebagai tersangka, meskipun tindakan tersebut merupakan respons spontan untuk mempertahankan keselamatan diri dan orang lain.
Kondisi ini bukan sekadar kontroversi publik, tetapi menyentuh persoalan mendasar arah sistem peradilan pidana. Ketika seseorang diserang secara melawan hukum namun negara merespons dengan mempidanakan pihak yang bertahan, hukum berisiko kehilangan fungsinya sebagai instrumen perlindungan.
Salah satu kasus yang ramai diperbincangkan terjadi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, ketika seorang suami mengejar pelaku jambret yang merampas tas istrinya. Dalam peristiwa tersebut, pelaku meninggal dunia dan pihak korban kemudian diproses secara pidana. Publik memandang korban bertindak dalam situasi ancaman nyata, tetapi proses hukum justru bergerak cepat terhadap pihak yang semula menjadi target kejahatan.
Kasus serupa juga muncul dalam berbagai peristiwa pembegalan jalanan. Ketika korban melakukan perlawanan dan pelaku mengalami luka berat atau kematian, korban justru diposisikan sebagai pelaku tindak pidana. Hukum seakan gagal membedakan antara agresor dan pihak yang bertahan hidup.
Noodweer sebagai Prinsip Perlindungan
Dalam hukum pidana nasional terbaru, perlindungan terhadap korban seharusnya menjadi prinsip utama. Konsep pembelaan terpaksa atau noodweer diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan ini menyatakan bahwa seseorang tidak dipidana apabila terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri, orang lain, maupun harta benda.
Dalam perkara begal dan penjambretan, struktur peristiwanya jelas: terdapat agresor, ancaman seketika, dan tindakan korban sebagai respons bertahan. Dasar yang relevan bukanlah pemidanaan korban, melainkan penerapan noodweer sebagai alasan pembenar.
Namun praktik penegakan hukum kerap bergerak secara formalistik. Aparat sering menilai peristiwa dari akibat yang tampak, seperti adanya luka atau kematian, lalu segera menerapkan pasal penganiayaan tanpa terlebih dahulu menempatkan korban dalam konteks serangan yang mendahuluinya. Muncul kecenderungan “tersangka terlebih dahulu, pembelaan belakangan.”
Padahal pembelaan terpaksa seharusnya dipertimbangkan sejak tahap awal penyidikan, bukan hanya diuji di akhir proses.
Noodweer Excess dan Overmacht
Perdebatan sering muncul ketika pembelaan diri dinilai melampaui proporsi. KUHP Nasional melalui Pasal 43 mengatur konsep noodweer excess, yakni pembelaan yang melampaui batas kewajaran akibat keguncangan jiwa hebat karena serangan seketika yang melawan hukum, dan tetap tidak dipidana.
Berbeda dengan itu, Pasal 42 mengatur overmacht atau daya paksa. Konsep ini berlaku dalam situasi pemaksaan yang bukan merupakan pembelaan terhadap agresor. Dalam kasus begal, karena terdapat serangan langsung, kerangka yang tepat adalah noodweer, bukan overmacht.
Penegakan Hukum Berorientasi Perlindungan
Pemidanaan korban menunjukkan persoalan lebih serius: kegagalan menghadirkan rasa aman, lalu korban dibebani konsekuensi hukum saat ia bertahan hidup. Dalam negara hukum, tidak dapat dibenarkan apabila warga yang diserang justru dihukum karena negara terlambat atau absen dalam perlindungan.
Penerapan noodweer sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 KUHP Nasional harus ditegakkan sebagai instrumen perlindungan nyata. Jika korban terus diproses pidana dalam situasi darurat, maka sistem hukum berisiko berubah dari pelindung masyarakat menjadi ancaman kedua setelah kejahatan itu sendiri.